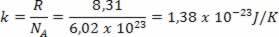Sejak awal Peradaban, kematian dianggap sebagai aspek yang mempesona dan, pada saat yang sama, menakutkan umat manusia. Kematian dan peristiwa yang terjadi setelahnya, secara historis, merupakan sumber inspirasi bagi doktrin filosofis dan religius, serta sumber ketakutan, kesedihan, dan kecemasan yang tiada habisnya bagi makhluk manusia.
Ketertarikan pada topik kematian dimulai dengan membaca beberapa laporan dari LELU (Laboratorium Studi dan Intervensi Duka). Kontak dengan laporan-laporan ini, dan analisis kematian sebagai fenomena psikis, adalah titik awal dari karya ini. Artikel-artikel itu menentang kerinduan alami tentang kematian dan menunjukkan bahwa, terlepas dari dimensi halus yang dimiliki kematian. psikis, ada profesional dan entitas yang berkomitmen untuk mempelajarinya dengan cara ilmiah, menggunakan metodologi pada dasarnya psikologis.
Karena kontak awal dengan materi LELU dan minat yang ditimbulkannya, pencarian untuk yang lain penelitian yang sudah dilakukan di bidang yang sama adalah dorongan alami, dan akhirnya membentuk landasan teoretis yang mendukung ini kerja.
Kematian sebagai fenomena fisik telah dipelajari secara ekstensif dan terus menjadi subjek penelitian, tetapi tetap menjadi misteri yang tak tertembus ketika kita menjelajah ke ranah jiwa.
Berbicara tentang kematian, sambil membantu menguraikan gagasan keterbatasan manusia, memprovokasi tertentu ketidaknyamanan, karena kita berhadap-hadapan dengan keterbatasan yang sama, yang tak terelakkan, kepastian bahwa suatu hari kehidupan akan datang sampai akhir.
Kepastian kematian manusia memicu serangkaian mekanisme psikologis. Dan mekanisme inilah yang memicu keingintahuan ilmiah kita. Dengan kata lain, fokus perhatian adalah bagaimana manusia menghadapi kematian; ketakutan mereka, kecemasan mereka, pertahanan mereka, sikap mereka terhadap kematian.
Tujuan dari penelitian ini adalah pendalaman teoritis tentang masalah kematian, dengan fokus pada cara pria menghadapi fenomena manusia yang tak terelakkan ini, menyadari mekanisme psikologis yang ikut bermain ketika manusia dihadapkan pada kematian.
Subjek kematian sama sekali bukan diskusi saat ini. Banyak filsuf, sejarawan, sosiolog, ahli biologi, antropolog, dan psikolog telah membahas masalah ini sepanjang sejarah. Ini karena kematian bukanlah bagian dari kategori tertentu; itu adalah pertanyaan yang berjalan sepanjang sejarah, di atas semua itu adalah pertanyaan yang pada dasarnya manusiawi.
Dalam berbagai pendekatan teoretis yang memungkinkan refleksi tentang kematian, salah satunya menarik bagi kami: pendekatan psikoanalitik. Pendekatan inilah yang memberi substansi pada pertanyaan kita tentang kematian, baik melalui analisis pribadi atau melalui teori itu sendiri.
Konsepsi yang dimiliki seseorang tentang kematian dan sikap manusia terhadap kematian cenderung berubah sesuai dengan konteks sejarah dan budaya. Tidak diragukan lagi, munculnya kapitalisme dan masa-masa krisisnya memunculkan pandangan baru tentang kematian, yang menurut Torres, (1983), berkaitan dengan munculnya kapital sebagai kekuatan utama produksi. Dalam pengertian ini, yang hidup dapat melakukan apa saja dan yang mati tidak dapat berbuat apa-apa, karena kehidupan produktif mereka telah terputus.
Menghadapi krisis ini, di mana manusia mendapati diri mereka benar-benar ditinggalkan dan tidak siap, kami melihat pendalaman teoretis ini sebagai cara untuk mengukur kematian, berkontribusi pada pemahaman dan elaborasi yang lebih baik, terutama memperlengkapi profesional kesehatan, yang bekerja berdampingan dengan ini tema.
Karya ini disusun dalam tiga bagian utama. Yang pertama berusaha untuk menganalisis dampak kematian pada masyarakat dari waktu ke waktu, menunjukkan bagaimana masyarakat yang berbeda pada waktu yang berbeda menangani masalah ini. Bagian kedua berbicara tentang perasaan ambigu yang dihasilkan dalam diri kita, manusia, ketika kita dipaksa untuk menghadapi kematian kita sendiri, serta kematian orang lain. Bagian ketiga dan terakhir berbicara tentang kesedihan dalam konteks yang berbeda.
DATA HISTORIS
Kami memiliki warisan budaya tentang kematian yang mendefinisikan pandangan kami tentang kematian hari ini. Menurut Kastenbaum dan Aisenberg (1983), interpretasi saat ini tentang kematian adalah bagian dari warisan yang diwariskan generasi sebelumnya dan budaya kuno kepada kita.
Kami kemudian akan berjalan-jalan singkat melalui sejarah sehingga kami dapat memahami bagaimana ide kematian yang ditemukan hari ini dibangun.
Para arkeolog dan antropolog, melalui studi mereka, menemukan bahwa manusia Neanderthal sudah peduli dengan kematiannya:
"Manusia Neanderthal tidak hanya menguburkan mayatnya, tetapi dia terkadang mengumpulkan mereka (Gua Anak-anak, dekat Menton)." Morin (1997)
Juga menurut Morin (1997) dalam prasejarah, kematian orang-orang Musterense ditutupi oleh batu, terutama di wajah dan kepala, baik untuk melindungi mayat hewan, dan untuk mencegah mereka kembali ke dunia hidup. Kemudian, makanan dan senjata disimpan di kuburan batu dan kerangkanya dicat dengan zat merah.
“Tidak meninggalkan orang mati menyiratkan kelangsungan hidup mereka. Tidak ada laporan tentang kelompok kuno yang meninggalkan orang mati atau meninggalkan mereka tanpa upacara.” Morin (1997)
Bahkan hari ini, di dataran tinggi Madagaskar, sepanjang hidup mereka, para kibori membangun rumah bata, tempat di mana tubuh mereka akan tetap berada setelah kematian.
Menurut Kastenbaum dan Aisenberg (1983), orang Mesir kuno, dalam masyarakat mereka yang sangat maju dari sudut pandang intelektual dan teknologi, mereka menganggap kematian sebagai kejadian dalam lingkup tindakan. Mereka memiliki sistem yang bertujuan untuk mengajar setiap individu untuk berpikir, merasakan dan bertindak dalam kaitannya dengan kematian.
Para penulis melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang Melayu, yang hidup dalam sistem komunitas yang intens, menghargai kematian suatu komponen, sebagai kerugian bagi kelompok itu sendiri. Kali ini, sebuah karya ratapan kolektif dalam menghadapi kematian diperlukan bagi para penyintas. Lebih jauh lagi, kematian dipandang bukan sebagai peristiwa yang tiba-tiba, tetapi sebagai proses yang harus dialami oleh seluruh masyarakat.
Menurut Aries (1977), dalam Vulgata, kitab Kebijaksanaan, setelah kematian, orang benar akan pergi ke Firdaus. Buku Kebijaksanaan versi Nordik menolak gagasan Surga yang dijelaskan dalam buku aslinya. karena, menurut para penerjemah, orang Nordik tidak mengharapkan kesenangan yang sama seperti orang Timur setelah kematian. Ini karena orang Timur menggambarkan surga sebagai “kesejukan naungan”, sedangkan orang Nordik lebih suka “kehangatan matahari”. Keingintahuan ini menunjukkan kepada kita bagaimana manusia ingin, setidaknya setelah kematian, untuk mendapatkan kenyamanan yang tidak mereka dapatkan dalam hidup.
Buddhisme, melalui mitologinya, berusaha untuk menegaskan keniscayaan kematian. Doktrin Buddhis memberi tahu kita "Perumpamaan Butir Sesawi": seorang wanita dengan anaknya yang sudah meninggal di lengannya mencari Buddha dan memohonnya untuk dihidupkan kembali. Buddha meminta wanita itu untuk mendapatkan beberapa biji sesawi untuk menghidupkannya kembali. Namun, wanita itu harus mendapatkan biji-bijian ini di rumah yang belum pernah ada orang yang meninggal. Jelas rumah ini tidak ditemukan dan wanita itu mengerti bahwa dia harus selalu mengandalkan kematian.
Dalam mitologi Hindu, kematian dipandang sebagai katup pelarian untuk kontrol demografis. Ketika "Ibu Pertiwi" menjadi kelebihan beban dengan orang-orang yang hidup, dia memohon kepada dewa Brahma yang kemudian mengirimkan "wanita berbaju merah" (yang mewakili kematian dalam mitologi Barat) untuk mengambil orang, sehingga mengurangi sumber daya alam dan populasi yang berlebihan dari "Ibu Bumi".
Menurut Mircea Eliade (1987), Finno-Ugrics (orang-orang dari Semenanjung Kola dan Siberia Barat) memiliki religiositas yang sangat terkait dengan perdukunan. Orang-orang mati dari orang-orang ini dimakamkan di kuburan keluarga, di mana mereka yang meninggal lebih lama menerima "yang baru mati". Jadi, keluarga terdiri dari yang hidup dan yang mati.
Contoh-contoh ini memberi kita gagasan tentang kontinuitas dalam kaitannya dengan kematian, yang tidak sama, dianggap sebagai tujuan itu sendiri. Ada upaya tertentu pada kontrol magis atas kematian, yang memfasilitasi integrasi psikologisnya, sehingga tidak memiliki pemisahan yang tiba-tiba antara hidup dan mati. Ini tidak diragukan lagi membawa manusia lebih dekat ke kematian dengan lebih sedikit teror.
Terlepas dari keakraban mereka dengan kematian, Orang Kuno Konstantinopel menjauhkan kuburan dari kota dan desa. Kultus dan penghormatan yang mereka berikan kepada orang mati dimaksudkan untuk menjauhkan mereka, sehingga mereka tidak akan "kembali" untuk mengganggu yang hidup.
Di sisi lain, pada Abad Pertengahan, pemakaman Kristen terletak di dalam dan di sekitar gereja dan kata pemakaman juga berarti "tempat di mana Anda tidak lagi mengubur". Oleh karena itu, parit-parit yang penuh dengan tulang yang tumpang tindih dan terbuka di sekitar gereja sangat umum.
Abad Pertengahan adalah masa krisis sosial yang intens, yang akhirnya menandai perubahan radikal dalam cara manusia menghadapi kematian. Kastenbaum dan Aisenberg (1983) memberi tahu kita bahwa masyarakat abad keempat belas dilanda wabah, kelaparan, perang salib, Inkuisisi; serangkaian peristiwa yang menyebabkan kematian massal. Kurangnya kontrol atas peristiwa sosial juga tercermin dalam kematian, yang tidak bisa lagi dikendalikan secara ajaib seperti di masa-masa sebelumnya. Sebaliknya, kematian datang untuk hidup berdampingan dengan manusia sebagai ancaman yang terus menghantui dan mengejutkan semua orang.
Kurangnya kontrol ini membawa kesadaran manusia pada saat ini, ketakutan akan kematian. Dari sana, serangkaian konten negatif mulai dikaitkan dengan kematian: konten sesat, mengerikan, serta penyiksaan dan pencambukan mulai berhubungan dengan kematian, menyebabkan keterasingan total manusia dalam menghadapi peristiwa ini jadi mengganggu. Kematian dipersonifikasikan sebagai cara bagi manusia untuk mencoba memahami dengan siapa dia berhadapan, dan serangkaian gambar artistik ditahbiskan sebagai simbol kematian yang sebenarnya, melintasi waktu hingga hari-hari hari ini.
Kübler-Ross (1997) menjelaskan bahwa perubahan sosial semakin intens dan cepat, yang diekspresikan oleh kemajuan teknologi. Manusia menjadi semakin individualistis, tidak terlalu mengkhawatirkan masalah-masalah komunitas. Perubahan-perubahan ini berdampak pada cara manusia menghadapi kematian saat ini.
Manusia hari ini hidup dengan gagasan bahwa bom bisa jatuh dari langit kapan saja. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa manusia, yang dihadapkan dengan begitu banyak kekurangan kendali atas kehidupan, mencoba membela diri secara psikis, dengan cara yang semakin intens, melawan kematian. "Menurunkan kapasitas pertahanan fisik Anda setiap hari, pertahanan psikologis Anda bertindak dalam berbagai cara" Kübler-Ross (1997)
Pada saat yang sama, kekejaman ini, menurut sudut pandang Mannoni, (1995), merupakan dorongan kehancuran yang sebenarnya; dimensi yang terlihat dari dorongan kematian.
Mannoni (1995), mengutip Aries, mengatakan bahwa kematian mengungkapkan korelasinya dengan kehidupan di berbagai momen sejarah. Orang bisa memilih di mana mereka akan mati; jauh atau dekat orang-orang tersebut, di tempat asal mereka; meninggalkan pesan kepada keturunan mereka.
Kemungkinan memilih menimbulkan hilangnya martabat yang semakin besar ketika sekarat, seperti yang dikatakan Kübler-Ross kepada kita (1997): "... Lewatlah sudah hari-hari ketika seorang pria diizinkan untuk mati dengan damai dan bermartabat dalam dirinya sendiri rumah."
Bagi Mannoni, saat ini, 70% pasien meninggal di rumah sakit, sedangkan pada abad terakhir, 90% meninggal di rumah, dekat dengan keluarga mereka. Ini karena, dalam masyarakat Barat, orang yang sekarat biasanya disingkirkan dari lingkaran keluarga mereka.
“Dokter tidak menerima bahwa pasiennya meninggal dan, jika ia memasuki bidang di mana impotensi medis diakui, godaan untuk memanggil dokter. ambulans (untuk menyingkirkan "kasus") akan muncul sebelum ide menemani pasien di rumah, sampai akhir hayat." manoni (1995)
Kematian alami memberi jalan untuk kematian yang dipantau dan upaya resusitasi. Seringkali, pasien bahkan tidak diajak berkonsultasi tentang apa yang ingin dia coba untuk membebaskannya. Medikalisasi kematian dan perawatan paliatif seringkali hanya berfungsi untuk memperpanjang penderitaan pasien dan keluarganya. Sangat penting bagi tim medis untuk belajar membedakan perawatan paliatif dan kenyamanan untuk pasien sekarat dari perpanjangan hidup yang sederhana.
Aspek perilaku manusia lainnya dalam kaitannya dengan kematian adalah bahwa di masa lalu, orang lebih suka mati perlahan, dekat dengan keluarga, di mana orang yang sekarat memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat ini, tidak jarang mendengar bahwa kematian instan lebih disukai daripada penderitaan panjang yang disebabkan oleh suatu penyakit.
Namun, menurut Kovács (1997), bertentangan dengan akal sehat, waktu penyakit, justru membantu mengasimilasi gagasan kematian, dan untuk dapat membuat keputusan nyata, seperti mengadopsi anak atau menyelesaikannya perbedaan pendapat.
Menurut Bromberg (1994) budaya kita tidak memasukkan kematian sebagai bagian dari kehidupan, melainkan sebagai hukuman atau hukuman.
PRIA YANG MENGHADAPI KEMATIAN SENDIRI / PRIA YANG MENGHADAPI KEMATIAN ORANG LAIN
Sejak usia sangat dini, sebagai bayi, ketika kita mulai membedakan tubuh kita sendiri dari tubuh ibu, kita dipaksa untuk belajar memisahkan diri dari siapa atau apa yang kita cintai. Pada awalnya, kami hidup dengan perpisahan sementara, seperti pindah sekolah. Tetapi ada saatnya, ketika kehilangan pertama kita yang pasti terjadi: seseorang yang sangat kita sayangi suatu hari pergi selamanya. Justru "selamanya" inilah yang paling mengganggu kita.
Namun, semakin kita sadar akan kematian kita sehari-hari, semakin kita bersiap untuk saat kehilangan segalanya. yang kita kumpulkan dan pelihara sepanjang hidup: dari semua beban intelektual, semua hubungan afektif, hingga tubuh fisikawan.
Dengan semakin jauhnya jarak manusia dalam kaitannya dengan kematian, terciptalah tabu, seolah-olah tidak dianjurkan atau bahkan dilarang untuk membicarakan topik ini.
Menurut Bromberg (1994) “seperti yang kita pelajari dalam budaya kita, kita menghindari rasa sakit, kita menghindari kehilangan dan kita lari dari kematian, atau kita berpikir untuk lari darinya...”
Gambaran saat ini mengungkapkan dimensi perpecahan yang telah dibuat manusia antara hidup dan mati, berusaha menjauh dari gagasan kematian, selalu mempertimbangkan bahwa orang lainlah yang akan mati dan bukan dia. Kami kemudian melontarkan pertanyaan tentang penderitaan dan ketakutan sehubungan dengan kematian.
Salah satu keterbatasan dasar manusia adalah keterbatasan waktu. Menurut Torres (1983): "... waktu menghasilkan kesedihan, karena dari sudut pandang temporal, faktor pembatas yang besar disebut kematian..."
Psikoanalisis Eksistensial, yang ditunjukkan oleh Torres (1983) mengungkapkan dimensi penderitaan kematian: "Kepedihan dalam diri kita mengungkapkan kematian dan ketiadaan menentang kecenderungan terdalam dan paling tak terelakkan dari keberadaan kita", yang akan menjadi penegasan diri. sama.
Mannoni (1995) dalam Freud mencari kata-kata yang berbicara tentang penderitaan manusia dalam menghadapi kematian: "... Freud menempatkannya sebagai reaksi terhadap ancaman eksternal, atau sebagai melankolis, dalam proses internal. Namun, itu selalu merupakan proses yang terjadi antara diri dan tingkat keparahan superego."
Menurut Kastenbaum dan Aisenberg (1983) manusia berurusan dengan dua konsepsi dalam kaitannya dengan kematian: kematian yang lain, yang kita semua sadari, meskipun itu terkait dengan ketakutan akan ditinggalkan; dan konsepsi kematian itu sendiri, kesadaran akan keterbatasan, di mana kita menghindari berpikir karena, untuk ini, kita harus menghadapi yang tidak diketahui.
Ini adalah penderitaan yang ditimbulkan ketika bersentuhan dengan kematian yang mematikan, yang membuat manusia bergerak untuk mengatasinya, memicu untuk tujuan ini, berbagai mekanisme pertahanan, diekspresikan melalui fantasi bawah sadar tentang about kematian. Fantasi yang sangat umum adalah bahwa ada kehidupan setelah kematian; bahwa ada dunia surgawi, disiram oleh prinsip kesenangan dan di mana tidak ada penderitaan; ada kemungkinan kembali ke rahim ibu, semacam kelahiran terbalik, di mana tidak ada keinginan dan kebutuhan. Tidak seperti fantasi yang menyenangkan ini, ada fantasi yang membangkitkan rasa takut. Individu dapat menghubungkan kematian dengan neraka. Mereka adalah fantasi penganiayaan yang berkaitan dengan perasaan bersalah dan penyesalan. Selain itu, ada identifikasi proyektif dengan tokoh jahat, yang menghubungkan kematian dengan makhluk menakutkan, berwajah tengkorak, terjalin dengan ketakutan akan pemusnahan, disintegrasi dan pembubaran.
Manusia adalah satu-satunya hewan yang menyadari kematiannya sendiri. Menurut Kovács (1998): "Ketakutan adalah respons paling umum terhadap kematian. Ketakutan akan kematian bersifat universal dan mempengaruhi semua manusia, tanpa memandang usia, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi dan keyakinan agama."
Untuk Psikoanalisis Eksistensial yang diucapkan oleh Torres, (1983): "... ketakutan akan kematian adalah ketakutan dasar dan pada saat yang sama sumber dari semua pencapaian kita: semua yang kita lakukan adalah melampaui kematian.”
Ini melengkapi pemikiran ini dengan menyatakan bahwa "semua tahap perkembangan sebenarnya adalah bentuk protes universal terhadap kecelakaan kematian."
Menurut Freud (1917) tidak ada yang percaya pada kematian mereka sendiri. Tanpa disadari, kita yakin akan keabadian kita sendiri. “Kebiasaan kami adalah menekankan penyebab kematian yang kebetulan – kecelakaan, penyakit, usia tua; dengan cara ini, kami mengkhianati upaya untuk mengurangi kematian dari kebutuhan menjadi peristiwa kebetulan.”
Sumber: Sekolah Brasil - https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/estudo-teorico-morte.htm